Read more »
Senja di Pinggir Sungai Bambu: Renungan Tauhid dan Makna Hidup
Dalam suasana itu, hati ini pelan-pelan berbicara. Alam menjadi cermin yang memantulkan banyak pelajaran. Bambu yang tumbuh menjulang mengajarkanku tentang keikhlasan: ia tumbuh lurus ke langit, tidak pernah meminta pujian, tidak butuh pengakuan. Sungai yang mengalir tanpa henti mengajarkan ketekunan: meski seringkali tidak diperhatikan, ia tetap memberi kehidupan. Dan ikan yang kini kupanggang mengajarkan tentang rezeki: ia datang bukan hanya karena kailku, tapi karena izin dari Sang Pemilik Kehidupan.
Semua ini membawaku pada satu kesadaran mendalam: hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menyadari bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan. Inilah makna dari tauhid yang sejati. Menyadari bahwa segala sesuatu, dari sekecil daun hingga sebesar semesta, berada dalam genggaman Allah. Tidak ada satu pun yang luput dari pengaturan-Nya. Termasuk diriku sendiri, yang hari ini diberi kesempatan untuk duduk tenang di antara pohon bambu, menikmati hasil jerih payah yang pada hakikatnya bukan benar-benar milikku.
Kesadaran itu menembus hingga ke dalam jiwa. Ini bukan tentang filsafat yang rumit, tetapi tentang kebeningan hati dalam menerima. Ketika kita sadar bahwa semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya, maka hati menjadi ringan. Tidak ada yang perlu dikejar secara berlebihan. Tidak ada yang perlu ditakuti secara berlebihan. Cukup jalani hidup dengan cinta, dengan syukur, dan dengan kehadiran penuh. Itulah ajaran tasawuf dalam kehidupan nyata—bukan sekadar teori, tapi praktik keikhlasan di setiap helaan napas.
Senja semakin merunduk. Langit berubah jingga, lalu perlahan menjadi kelabu. Burung-burung kembali ke sarangnya. Angin mulai lebih dingin. Di saat-saat seperti ini, aku sadar bahwa waktu tidak akan pernah kembali. Seperti matahari yang tenggelam, setiap hari dalam hidup kita juga akan berlalu, membawa kita satu langkah lebih dekat kepada akhir. Tapi bukan akhir yang menakutkan, melainkan kepulangan. Dan betapa indahnya jika kita kembali kepada-Nya dalam keadaan bersih, setelah menjalani hidup dengan kesadaran bahwa semuanya dari-Nya, untuk-Nya.
Sore itu bukan hanya tentang makan ikan bakar di tepi sungai. Bukan hanya tentang menikmati angin dan melihat daun bambu melambai. Tapi tentang merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detail kecil kehidupan. Ketika kita bisa melihat Allah dalam hembusan angin, dalam suara air, dalam rasa syukur atas sepotong rezeki, maka saat itulah kita sedang benar-benar hidup. Karena hidup yang sesungguhnya bukan diukur dari apa yang terlihat, tetapi dari sejauh mana hati kita terhubung kepada-Nya.
Kesederhanaan itu ternyata menyimpan kedalaman. Dalam diam, aku menemukan makna. Dalam makna, aku menemukan Tuhan. Dan dalam Tuhan, aku menemukan diriku sendiri.
Hari mulai gelap. Cahaya terakhir matahari perlahan ditelan cakrawala. Tapi di hatiku, justru terang mulai menyala. Ada kehangatan yang tak berasal dari api, ada kenyamanan yang tak berasal dari benda. Semua itu datang dari kesadaran akan keberadaan-Nya—yang Maha Dekat, lebih dekat dari urat leherku sendiri.
Aku teringat akan banyak hari yang telah kulewati dalam kesibukan, dalam hiruk pikuk dunia yang seringkali membutakan hati. Di kota, suara klakson lebih sering kudengar dibanding suara alam. Pandangan lebih banyak tertuju pada layar gawai dibandingkan wajah orang-orang di sekitar. Hidup menjadi terburu-buru, seperti sedang berlomba tanpa arah yang pasti. Tapi di sini, di tepian sungai ini, semuanya menjadi jelas. Seolah semesta bersatu untuk membisikkan bahwa hidup bukan soal cepat atau lambat, tapi soal sadar atau lalai.
Perlahan, kuangkat ikan yang telah matang. Aromanya menguar ke udara, bersatu dengan harum tanah basah dan kayu yang mulai lembap. Setiap kunyahan menjadi doa. Setiap rasa menjadi pengingat akan nikmat yang seringkali terlupakan. Inilah rezeki yang paling murni: bukan yang berlimpah, tapi yang disyukuri.
Aku jadi teringat akan nasihat orang tua: “Jangan hanya mencari hidup yang besar, tapi carilah hidup yang dalam.” Dulu kalimat itu terasa samar, tapi kini aku mulai mengerti. Hidup yang besar bisa terlihat oleh banyak orang—pangkat, jabatan, gelar, harta. Tapi hidup yang dalam hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Ia tenang, tak mudah goyah, karena berakar pada makna, bukan pada tampilan.
Di sekelilingku, malam turun dengan pelan. Bulan mulai menampakkan wajahnya di balik sela-sela dedaunan. Bintang-bintang, seperti lentera kecil, menghiasi langit malam. Suasana semakin sunyi, tapi tidak sepi. Justru dalam sunyi seperti inilah, aku merasa paling terhubung—dengan diriku sendiri, dengan alam, dan dengan Tuhanku.
Aku merenungi kembali perjalanan hidupku. Berapa banyak waktu yang terbuang hanya karena mengejar hal-hal yang tak membawa kedamaian? Berapa banyak hubungan yang renggang hanya karena ego lebih dipertahankan daripada kasih sayang? Betapa sering aku lupa bahwa hidup ini hanya sebentar, bahwa tak ada yang dijamin selain kematian?
Namun malam ini aku tidak ingin menyesal. Aku hanya ingin memulai lagi. Dari tepian sungai yang sunyi ini, aku ingin kembali ke dalam diriku, menyusun ulang prioritas, dan melangkah dengan lebih sadar. Karena hidup tidak perlu sempurna, hanya perlu berarti.
Aku menyadari bahwa setiap manusia punya ruang sunyinya masing-masing. Tempat di mana ia bisa berbicara dengan jiwanya, mendengar suara nuraninya, dan menyentuh jejak kehadiran Tuhan. Bagi sebagian orang, ruang itu adalah masjid. Bagi yang lain, mungkin kamar kecil di rumah. Bagiku malam ini, ruang sunyiku adalah alam ini—sungai, bambu, senja, dan kesadaran yang perlahan tumbuh dari keheningan.
Tasawuf mengajarkanku bahwa kedekatan dengan Tuhan bukan hanya lewat ibadah formal, tapi juga lewat kehadiran utuh dalam setiap detik hidup. Bahwa makan bisa menjadi zikir. Bahwa diam bisa menjadi doa. Bahwa melihat langit bisa menjadi bentuk tafakur. Dan bahwa hidup yang terhubung dengan Tuhan tidak membutuhkan banyak teori, hanya butuh hati yang bersih.

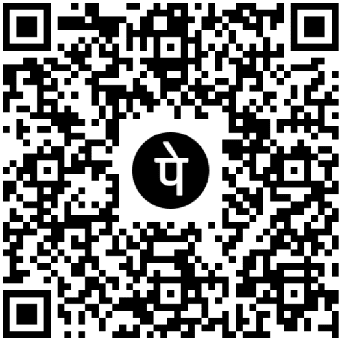






0 Reviews