Read more »
Bercerita Adalah Salah Satu Ungkapan Syukur
Sore itu, langit menua dalam semburat jingga yang lembut. Angin berdesir pelan menyusuri celah-celah batang bambu yang menjulang, mengeluarkan suara lirih yang menyerupai bisikan dzikir alam. Di tengah kebun bambu yang sepi, jauh dari riuh kota dan hiruk dunia, aku duduk bersila di atas tikar pandan yang mulai usang, ditemani secangkir teh hangat dan sunyi yang menenangkan.
Di tempat inilah, aku sering mengasingkan diri. Bukan karena membenci keramaian, tetapi karena ingin mendengar suara yang lebih dalam; suara dari dalam diri, dan mungkin, suara-Nya. Dan sore ini, seperti sore-sore yang lalu, aku kembali membuka ruang dalam hati untuk satu hal sederhana: bercerita.
Bercerita, bagiku, bukan sekadar menyusun kisah. Ia adalah cara hati menyampaikan rasa syukur atas segala yang telah Allah izinkan terjadi dalam hidup ini. Dalam suasana sunyi yang hanya ditemani rintik cahaya matahari sore yang menyelinap di antara dedaunan bambu, aku merasa betapa agungnya karunia bisa mengingat.
Setiap kisah yang terucap, tentang luka maupun tawa, tentang kegagalan maupun kemenangan, sejatinya adalah bentuk pengakuan: bahwa aku telah melalui semua itu karena-Nya, dan bersama-Nya. Tak ada kisah yang berdiri sendiri. Semua terjalin dalam takdir yang indah meski tak selalu mudah. Maka bercerita, menjadi zikir yang tak terucap dalam lafaz, tapi mengalir dalam makna.
Aku teringat sebuah kalimat dari seorang guru sufi, “Syukur bukan hanya dengan kata, tetapi dengan menyadari setiap detik yang telah kau lewati adalah hadiah.” Dan cerita—cerita yang jujur dari hati adalah bentuk kesadaran itu. Di dalamnya tersimpan rasa: “Ya Allah, aku pernah jatuh, tapi Kau tak pernah benar-benar membiarkanku sendiri.”
Bayang-bayang sore semakin memanjang, sinar mentari redup berkilau di sela batang bambu, menari pelan bersama angin. Di suasana seperti inilah, bercerita menjadi begitu sakral. Tak ada pendengar, selain diriku sendiri, langit yang terbuka, dan hati yang sedang mengingat kembali jejak-Nya.
Mungkin inilah yang dimaksud oleh para sufi ketika mereka berkata bahwa kesunyian adalah sekolah jiwa. Di tengah alam, dalam dekapan bambu-bambu yang tenang, kita kembali belajar mengenal diri, mengurai perjalanan, dan mengucap syukur dengan cara yang paling halus: bercerita.
Dan bila kau tanya, kepada siapa cerita itu diarahkan? Maka jawabku: kepada-Nya. Lewat untaian kenangan yang dituturkan perlahan, aku sedang berkata, “Ya Allah, aku masih mengingat, dan aku tak ingin lupa betapa besar kasih-Mu.”
Sore itu, di tengah kebun bambu yang menua bersama cahaya senja, aku tidak sedang menulis cerita baru. Aku hanya sedang menyusun syukur dari lembar-lembar kisah lama, yang kini aku sadari: semuanya adalah cara Allah mendidik hatiku.
Dan dalam keheningan yang damai itu, aku tahu, setiap cerita yang aku ucapkan… adalah pujian.
Karena di balik setiap kisah, ada jejak kasih-Nya yang tak pernah hilang. Dan menyadarinya, adalah syukur yang paling dalam.
Malam perlahan turun seperti selimut lembut yang
ditarik perlahan dari ujung langit. Sinar terakhir mentari telah lenyap,
digantikan kerlip bintang yang malu-malu muncul di balik awan tipis. Di tengah
remang cahaya itu, teh di cangkirku tinggal sisa, tapi hangatnya masih
bertahan, seperti sisa-sisa pelukan dalam ingatan. Dan aku masih duduk di sana,
memeluk diam, sambil terus bercerita—kali ini bukan dengan kata-kata, melainkan
dengan hati yang tenang.
Aku menyadari bahwa
tidak semua cerita harus diceritakan kepada manusia. Ada kisah-kisah yang
terlalu sakral, terlalu dalam, yang hanya layak dibisikkan kepada langit. Ada
luka yang sembuh bukan karena dibicarakan, tapi karena dipeluk dalam diam oleh
Yang Maha Mendengar. Dan ada kebahagiaan yang begitu murni, hingga bila diucap
pun terasa berkurang nilainya, seolah hanya pantas dirayakan dalam sujud dan
air mata syukur.
Aku belajar bahwa
bercerita bukan hanya soal mengurai peristiwa. Lebih dari itu, ia adalah upaya
merajut makna. Dalam setiap kisah, selalu ada pelajaran, dan dalam setiap pelajaran,
selalu ada sentuhan kasih Ilahi. Tak peduli seberapa pahit atau manis, jika
kita mampu duduk dan merenunginya dalam hening, maka kita sedang menapaki jalan
syukur yang hakiki.
Ada masa-masa dalam
hidupku yang begitu gelap, hingga aku merasa seperti tersesat di belantara
waktu. Tapi kini, saat aku melihat ke belakang, aku mengerti bahwa di setiap
gelap itu, ada cahaya kecil yang terus membimbingku—walau aku tidak sadar waktu
itu. Dan bercerita tentang masa-masa itu bukan untuk mengungkit luka, tapi untuk
bersaksi: bahwa Allah tak pernah menjauh, bahkan saat aku merasa sendirian.
Di antara desir
angin malam yang mulai dingin, aku kembali menyusun satu demi satu kenangan.
Ada tawa bersama orang-orang tercinta, ada tangis kehilangan, ada perjuangan
yang terasa sia-sia, dan ada kejutan-kejutan indah yang datang saat aku nyaris
menyerah. Semuanya hadir kembali, bukan untuk menyiksaku, tapi untuk meneguhkan
bahwa hidup ini adalah rangkaian pelajaran cinta dari-Nya.
Dan begitulah,
setiap kali aku menceritakan kembali jalan hidupku, meski hanya pada bintang
dan angin, aku seperti sedang menyalakan pelita di dalam dada. Aku sedang
mengingatkan diriku sendiri bahwa aku pernah kuat, karena ada kekuatan yang
lebih besar menopangku. Aku pernah lemah, tapi tidak hancur. Aku pernah
kehilangan, tapi tak pernah ditinggalkan.
Bercerita menjadi
semacam ibadah sunyi. Ia tidak membutuhkan panggung, tidak menuntut tepuk
tangan, dan tidak menunggu validasi. Ia cukup untuk diri sendiri—dan untuk
Tuhan. Dalam cerita, kita menyusun ulang makna, dan dalam makna, kita menemukan
kehadiran-Nya yang sering tersembunyi dalam peristiwa paling sederhana.
Kadang aku
berpikir, mungkin inilah sebabnya kenapa para nabi diberi kisah—agar umatnya
belajar bukan hanya dari hukum, tapi dari cerita. Karena cerita menyentuh jiwa,
menggetarkan nurani, dan membuat manusia merasa dilihat, dipahami, dan tidak
sendirian. Begitu juga kita, dalam cerita pribadi kita, ada kemungkinan menjadi
pelajaran bagi orang lain, bahkan jika kita tak pernah menyadarinya.
Suatu waktu, aku
pernah bercerita kepada seorang sahabat tentang masa-masa sulit yang pernah
kualami. Ia terdiam lama, lalu berkata, “Aku tidak tahu bahwa kau pernah
mengalami itu. Tapi sekarang aku tahu, dan aku merasa tidak sendirian lagi.”
Sejak saat itu, aku mengerti, bahwa terkadang syukur bisa menular lewat cerita.
Kita tidak sedang menggurui, kita hanya berbagi perjalanan—dan siapa tahu, dari
sana tumbuh harapan.
Malam semakin
larut, dan langit sepenuhnya hitam, dihiasi cahaya bulan yang menggantung
malu-malu di antara kelopak awan. Kebun bambu mulai hening sepenuhnya, hanya
suara alam yang tersisa, seperti denting lembut dzikir semesta. Aku pun mulai
beranjak, menggulung tikar, menyesap sisa teh yang kini dingin, lalu menatap
langit sekali lagi sebelum melangkah pergi.
Namun hatiku tak
benar-benar pergi dari tempat itu. Sebagian diriku tertinggal, menyatu dengan
angin dan tanah, menjadi bagian dari cerita yang kututurkan malam ini. Dan aku
tahu, esok atau lusa, aku akan kembali. Bukan karena aku sedang mencari
jawaban, tapi karena aku ingin terus bersyukur. Lewat cerita, lewat keheningan,
lewat mengingat.
Karena bercerita
adalah caraku berdoa.
Dan selama masih ada detak di dada, selama masih bisa mengenang, aku akan terus menyusun kata—bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tapi untuk merayakan bahwa aku masih diizinkan menjalani hidup ini. Masih diizinkan bersyukur, dalam bentuk paling sederhana: sebuah cerita.

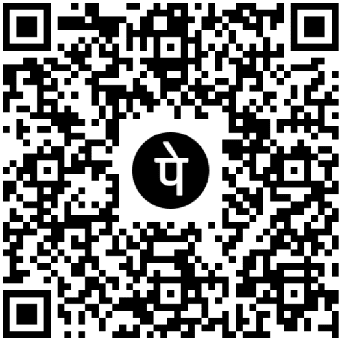






0 Reviews